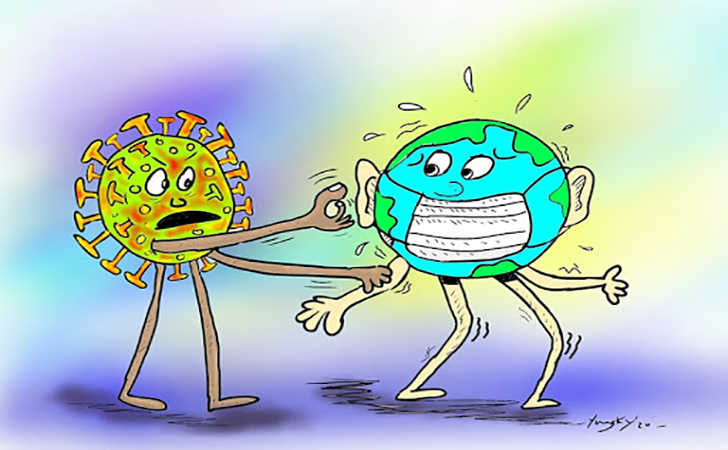Laporan: Indah Lestari
RIAUONLINE, PEKANBARU - Sepanjang sejarah kesusastraan dunia, negara rumpun Melayu seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, terkhusus Indonesia yang kaya akan sastra tulisan dan lisan memang jauh dari catatan Nobel.
Taufik Ikram Jamil, seorang Sastrawan asal Riau dalam bukunya berjudul Biar Mati Anak, Asal Jangan Mati Adat menceritakan tentang kegelisahan seorang temannya yang tanpa bisa melupakan bagaimana Bob Dylan dinyatakan sebagai pemenang Nobel Prize kategori Sastra pada 2016 lalu.
Bagi Taufik, Bob Dylan memang pantas mendapatkannya. Keunggulan aksara dalam lirik-lirik lagunya dan dendangan, baik lisan atau cara menyanyikan, yang khas membuat Nobel memilihnya untuk menerima hadiah di tahun itu.
Mungkin banyak orang-orang, khususnya peminat seni musik, sudah tak asing lagi dengan Blowin' in the Wind dan The Times They are A-Changin milik Bob Dylan.
Tak ada masalah dengan karya Bob Dylan atau pemenang Nobel sastra dunia lainnya yang menepikan telak kesusastraan lisan seperti syair dan juga pantun yang bahkan diakui kepentingan eksistensinya oleh UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization).
Masalahnya adalah cara pandang Nobel yang lebih terpaku pada tulisan atau aksara itu sendiri. Dengan kata lain, penuturan atau kreativitas dan keunikan dari seni-budaya tutur di sini tak menjadi penilaian utama. Sebut saja hanya berupa hiasan kecil atau sebagai nilai tambah saja jika diperlukan.
Penghargaan warisan Alfred Nobel yang telah ada sejak tahun 1901 tersebut, memang terkesan menutup sebelah mata terhadap ranah sastra daerah seperti lisan, terutama jika merujuk pada syair dan pantun, yang merupakan sastra lisan asal tanah Melayu.
Melirik Indonesia sendiri sebagai negara yang kaya akan bahasa dan tutur yang beragam, harusnya secara sastra yang dekat seolah satu ruh satu tubuh dengan bahasa. Indonesia mestinya jadi negara yang diperhitungkan dalam panggung Nobel. Terlebih untuk Provinsi Riau yang kaya akan khazanah peninggalan sejarah tulisan dan lisan, Bahasa Melayu yang juga menjadi hulu dan hilir dari sejarah Bahasa Indonesia.
Jika ingat, Tetralogi Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Toer yang digadang-gadang mampu menjadi pemenang Nobel beberapa tahun lalu, untuk karya seterkenal dan sepopuler itu saja, bahkan tak mampu membuat luluh dan kagum Nobel sampai saat ini. Apalagi sastra lisan murni yang mulai tak terawat dan tak dilirik lagi oleh muda-mudi bangsa. Harusnya, Nobel punya pandangan berbeda dari kaula muda pada awamnya. Sebab Nobel bicara kelas dunia, yang artinya punya standar pemikiran kritis dan penilaian yang tinggi. Bukan berdasarkan pada peluang pasar.
Mungkin di bidang sains atau ilmu pengetahuan seperti Fisika, Indonesia memang pernah mencatat sejarah Nobel. Tapi Fisika beda hal dengan Sastra. Fisika dinilai secara objektif dan pasti. Sedangkan, Sastra sebagai karya seni harus dinilai dari kreativitas dan secara kritis. Melihat unsur antara seni dan budaya secara mendalam serta utuh.
Sastra modern, seperti Barat, memang membuat banyak orang tergila-gila dan dominan digandrungi. Tetapi, perlu diingat bahwa tak ada salahnya menyeimbangkan modernitas dan tradisional sehingga dapat sama-sama dilirik. Sebab keduanya sama-sama bertumpu dari yang tradisional, kemudian baru menuju modern. Tidak ada yang pantas diasingkan atau ditepikan. Keduanya sama karya yang berharga. Butuh ketajaman logika dan intuisi untuk memandangnya.
Seorang sarjana Universitas Leiden-Belanda, Dr. Will Derks, dari Kajian Studi Indonesia berpendapat, bahwa faktor kelisanan yang penting dalam sastra Indonesia-Melayu tersebut punya keindahan tutur dan keunikan tersendiri sebagai budaya Timur terhadap karya Barat.
Sistem kesusasteraan di Barat yang bertumpu pada teks, memang cenderung mengabaikan kelisanan. Besar kemungkinan, atas alasan itu pulalah Nobel sendiri tak mampu menjangkau keberadaan dan nilai yang besar pada sastra dalam bahasa rumpun Melayu Indonesia, yang diperkirakan dipakai sekitar 300 juta jiwa manusia di muka bumi. Bahkan, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara termasuk rumpun Melayu telah dipelajari cukup banyak negara, seperti Belanda, Jepang, Australia, Kanada, dan Ukraina.
Rotterdam, Belanda, salah satunya. Kegairahan masyarakat Rotterdam menyaksikan kelisanan seperti pembacaan sajak, musikalisasi puisi, drama dan teater, menunjukkan ketertarikan dan kesadaran besar atas pentingnya kelisanan bagi ruang sastra dunia.
Sastra lisan berupa syair atau puisi karya Sutardji Calzoum Bahri (SCB) misalnya, sosok yang dikenal dengan Presiden Penyair Indonesia. Bentuk dari karya sastranya begitu terasa dalam pelestarian kelisanan. Ketunakan SCB dan ciri khas karyanya telah mengenalkan banyak hal tentang rapalan-rapalan dan mantra-mantra, serta tutur-tutur kemelayuan.
Tak hanya puisi, pantun tak kalah mengejutkan dan membanggakan sebagai sastra lisan. Seorang pengarang Prancis masyhur bernama Victor Hugo dalam catatannya untuk buku Marsden: Les Orientales (1829), menerbitkan versi Prancis terjemahan Ernest Founiet yang mana buku itu adalah pantun berkait (lanjutan) dari buku Marsden tersebut.
Mulai dari sana, di tahun-tahun berikutnya pengarang Perancis berbondong-bondong memasuki dunia kepenyairan dalam hal pantoums (pantun-pantun). Leconte de Lisle, menerbitkan 5 pantoum dalam bukunya Poeme Tragiques (1884). Charles Baudelaire dengan buku bergaya puitika pantoum (ibid) berjudul Harmonie du Soir. Memang tidak sesempurna pelisanan Melayu Indonesia, tetapi menjadi kebanggan besar atas bentuk apresiasi luar biasa terhadap kelisanan sendiri yang menjadi ciri khas bangsa ini.
Apresiasi itu juga memantik sanjungan yang datang dari seorang tokoh guru besar musik di Monash University, Margaret J. Kartonomi yang mengakui kekayaan bunyi atau kelisanan di Riau, Indonesia. Margaret menemukan ada lebih dari 100 ragam bunyi dalam musik Melayu Riau yang sulit ditemukan di belahan dunia lain, terlebih di era ini.
Sebut saja Riau Rhythm Chambers Indonesia (RRCI), sebuah klub musik asal Riau yang tunak membunyikan kelisanan Melayu dengan eksplorasi gaya musik Eropa modern. Hal ini juga upaya menjulang eksistensi lantunan nada-nada dan mantra-mantra Melayu agar bisa dikenal mancanegara. Meski dipoles kekinian dan bersahabat dengan era ini tapi, tidak sama sekali menghilangkan kemurnian dan keanggunan dari seni-budaya Melayu yang sesungguhnya.
Balik lagi ke sastra, dari sekian banyak jenis kelisanan yang ada. Terkhusus pantun. UNESCO menilai pantun memiliki arti penting bagi masyarakat Melayu. Bukan hanya sebagai alat komunikasi sosial, namun juga syarat akan nilai-nilai yang menjadi panduan moral. Pesan yang disampaikan melalui pantun umumnya menekankan keseimbangan dan harmoni hubungan antar manusia.
Dari sekian banyak sudut pandang dan fakta yang ada, harusnya Pantun mewakili sastra lisan, selain sebagai Warisan Budaya Tak Benda Dunia, juga layak mendapat ruang dalam lensa Nobel Prize terdahulu dan selanjutnya.